Masihkah Mapala Setia pada Akar Sejarahnya?
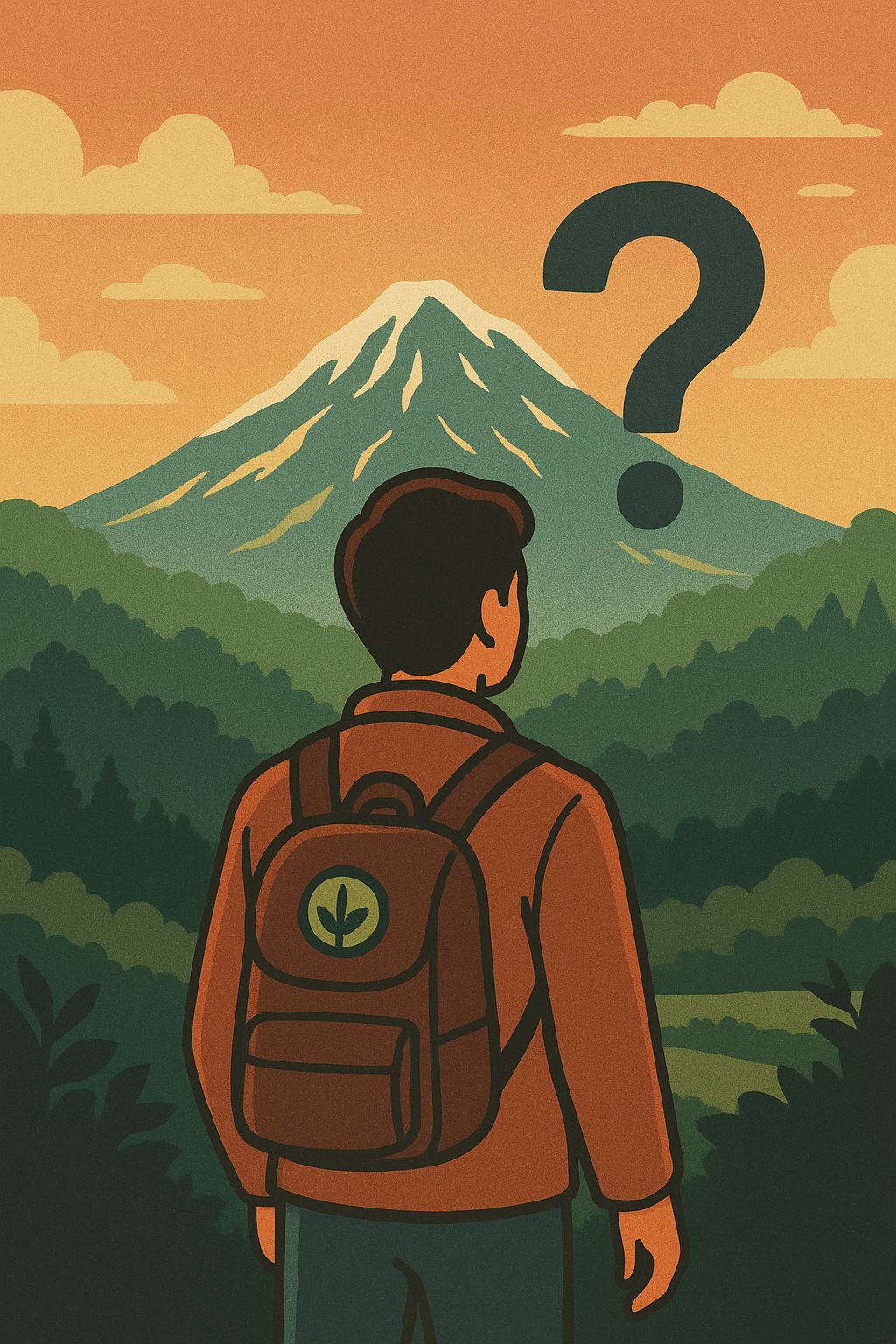
SENANDIKA.ID – Masihkan kita memahami Mapala sebagai rumah untuk belajar tentang alam dan kemanusiaan?
Sebagai bagian dari keluarga besar Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala), saya menyebut diri sebagai Mapala bukan sekadar menempel label organisasi, melainkan menjadikan ia sebagai identitas yang dulu sarat makna. Dari dalam tubuh organisasi inilah saya belajar arti tangguh, solidaritas, juga kecintaan terhadap lingkungan. Sejak awal berdiri, Mapala tidak pernah dimaksudkan hanya sebagai perkumpulan orang yang gemar naik gunung. Sejarah mencatat, pada 1960-an, Soe Hok Gie dan kawan-kawan menjadikan Mapala sebagai wadah belajar: alam adalah laboratorium hidup, tempat mahasiswa mengasah intelektualitas, kepekaan sosial, sekaligus nurani kemanusiaan.
Mapala lahir dari kegelisahan. Kegelisahan melihat realitas sosial, ketidakadilan, sekaligus kerusakan lingkungan. Aktivitas di alam bebas, mulai dari pendakian gunung hingga penjelajahan hutan, bukan tujuan akhir, melainkan sarana. Tujuannya lebih dalam: membentuk manusia yang kritis, solider, dan peduli. Inilah roh yang seharusnya tetap hidup dalam setiap generasi Mapala.
Kini, lebih dari setengah abad kemudian, wajah Mapala tampak berbeda. Di banyak kampus, Mapala sering kali dipersepsikan sekadar klub pendaki: kumpulan orang-orang yang menaklukkan puncak demi foto dan cerita. Tidak sedikit yang kehilangan akar cinta alam yang sejati. Padahal, pendakian seharusnya bukan tentang menaklukkan gunung, melainkan menaklukkan diri sendiri.
Ironisnya, pendidikan dasar (diksar) yang semestinya menjadi ruang pembentukan karakter, malah kerap identik dengan kekerasan fisik. Tradisi ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, seakan menjadi kebanggaan. Kita mendengar kisah peserta diksar yang sakit, bahkan ada yang meregang nyawa. Kekerasan semacam ini bukan hanya menyimpang dari nilai-nilai awal, tetapi juga merusak citra Mapala di mata publik. Diksar seharusnya melatih mental, disiplin, dan solidaritas, bukan menormalisasi kekerasan.
Namun, harus diakui pula bahwa tidak semua wajah Mapala suram. Di berbagai daerah, Mapala tetap hadir dengan kerja-kerja nyata untuk lingkungan: penanaman pohon, pembersihan sungai, edukasi masyarakat tentang sampah, hingga advokasi isu-isu lingkungan. Bahkan di tengah krisis iklim, Mapala masih menjadi salah satu elemen mahasiswa yang berani turun tangan langsung. Ini membuktikan bahwa idealisme awal belum sepenuhnya padam.
Sayangnya, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fenomena lain, sebagian anggota Mapala yang setelah lulus masuk ke lembaga tertentu, menjadikan isu lingkungan hanya sebagai komoditas. Alam berubah menjadi proyek, isu lingkungan menjadi ladang mencari uang. Ironis, ketika idealisme yang dulu menyala di hutan dan gunung kini redup di balik meja birokrasi. Padahal, Mapala semestinya melahirkan manusia yang teguh menjaga alam, bukan yang memperjualbelikannya.
Ironi lain justru muncul dari hal yang paling sederhana: menjaga kebersihan sekretariat. Tak jarang kita mendapati sekretariat Mapala yang berantakan, kumuh, dan jauh dari nilai hidup sehat. Padahal, bukankah kebersihan ruang kecil kita sendiri adalah cermin paling nyata dari cinta lingkungan? Jika hal sekecil itu saja gagal dijaga, bagaimana mungkin kita meyakinkan publik bahwa kita sanggup menjaga hutan, sungai, atau gunung?
Di tengah kerusakan hutan, banjir, krisis iklim, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat, Mapala seharusnya tampil di garda depan. Tidak hanya menjaga alam melalui aksi sporadis, melainkan konsisten meneguhkan diri sebagai gerakan mahasiswa pecinta alam dan manusia.
Sebagai seorang Mapala, saya menaruh harapan: semoga kita berani bercermin dan kembali ke akar. Mapala bukan sekadar cerita romantis mendaki gunung, bukan pula tradisi keras yang menyakiti. Mapala adalah laboratorium hidup, tempat kita belajar tentang empati, keberanian, dan tanggung jawab pada alam. Jika kita kehilangan itu semua, maka Mapala hanya tinggal nama tanpa makna.







