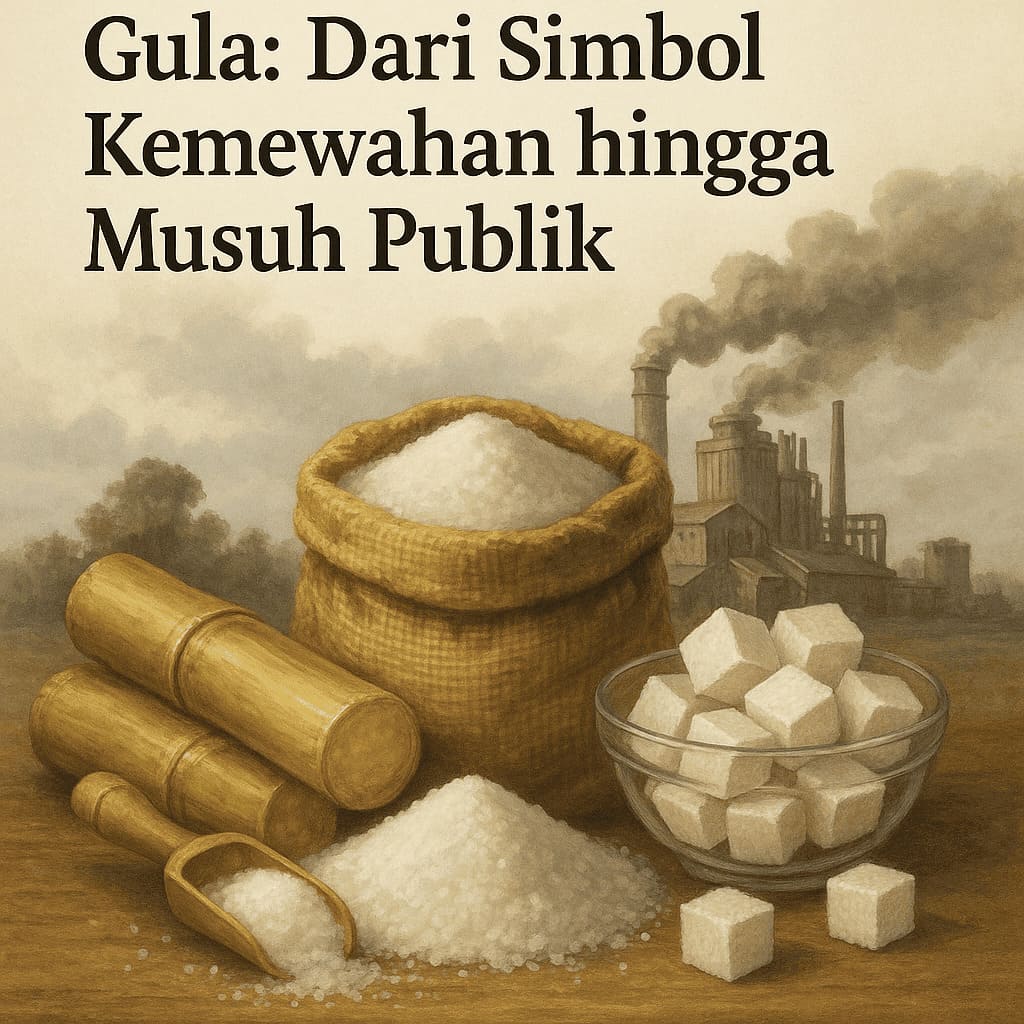
SENANDIKA.ID – Sejak kapan manis kehilangan maknanya, dan gula yang dulu dipuja dalam setiap sajiannya menjelma jadi biang keladi yang ditakuti di meja makan?
Oleh: Doni Onfire
Selain dikenal sebagai makanan bercita rasa manis, kini gula juga kerap diposisikan sebagai musuh bersama. Fenomena meningkatnya kasus diabetes melitus membuat banyak orang menghindari konsumsi gula sepenuhnya, bahkan ada yang sampai merasa fobia. Ketakutan ini sayangnya sering kali tidak berdasar. Banyak yang menganggap gula sebagai penyebab tunggal diabetes, padahal karbohidrat sederhana seperti nasi, roti, dan makanan ringan tinggi karbohidrat turut berkontribusi besar dalam meningkatkan kadar glukosa dalam darah.
Jejak Sejarah Gula dan Kapitalisme
Antropolog Sidney Mintz pernah mencatat bahwa gula bukan sekadar bahan makanan, melainkan simbol kekuatan dan status sosial. Sejak abad ke-19, kenikmatan rasa manis telah berkaitan erat dengan tumbuhnya kapitalisme modern. Kala itu, kelas menengah di Eropa mulai tumbuh pesat dan menuntut lebih banyak konsumsi makanan manis seperti kue, biskuit, dan puding.
Pada masa itu, belum ada teknologi penghalus gula yang memadai. Gula putih dianggap sebagai produk unggulan dan simbol keanggunan, bahkan menyimbolkan superioritas kulit putih Eropa. Namun, setelah abad ke-19, gula tak lagi menjadi barang mewah. Produksinya menjadi massal, berkat kerja keras buruh berupah rendah dalam sistem industri yang ketat. Gula pun beralih status: dari simbol elit menjadi konsumsi publik.
Putih, Manis, tapi Jadi Kambing Hitam
Di era modern, khususnya sejak 1960-an, industri pangan menciptakan bentuk gula baru: sirup jagung tinggi fruktosa (high-fructose corn syrup). Gabungan glukosa dan fruktosa ini dianggap banyak ahli sebagai bentuk gula yang paling berbahaya karena tidak memicu hormon leptin, yang memberi sinyal kenyang. Akibatnya, konsumsi berlebihan pun tak terhindarkan.
Fenomena ini kemudian berkembang menjadi tren kesehatan yang menciptakan kesadaran akan bahaya konsumsi gula berlebih. Sayangnya, kesadaran ini juga melahirkan ketakutan dan fobia kolektif terhadap makanan dan minuman manis. Di sisi lain, kondisi ini menciptakan pasar baru: produk “rendah gula” yang diklaim lebih sehat, namun kerap hanya mengurangi sebagian kandungan gula atau menggantinya dengan pemanis buatan seperti stevia, aspartam, atau sukralosa yang kadar manisnya bisa 200-300 kali lebih tinggi dari gula pasir.
Ironisnya, produsen bisa menjual produk ini dengan harga lebih tinggi, padahal biaya produksinya justru menurun akibat pengurangan bahan baku gula.
Benarkah Gula adalah Tersangka Utama Diabetes?
Menurut penelitian Matthew Pase dari Swinburne University, kadar gula darah yang meningkat justru dapat membantu meningkatkan daya ingat dan motivasi kerja pada orang dewasa yang lebih tua. Sementara itu, Dosen Ilmu Gizi dari Universitas Negeri Surabaya, Desty Muzarofatus Sholikhah, menegaskan bahwa diabetes tidak semata-mata disebabkan oleh konsumsi gula.
“Diabetes melitus adalah hasil dari gangguan metabolisme karbohidrat dan gaya hidup yang tidak sehat. Ini melibatkan kerja pankreas dan hormon insulin,” jelasnya. Glukosa jenis gula utama yang dibutuhkan tubuh bersumber dari karbohidrat dan merupakan bahan bakar penting untuk otak, otot, dan organ vital lainnya.
Masalah muncul ketika tubuh kelebihan asupan gula tanpa diimbangi aktivitas fisik yang memadai. Ketidakseimbangan ini membuat insulin kesulitan memproses glukosa, yang kemudian menumpuk dalam darah dan meningkatkan risiko diabetes.
Gula: Dua Sisi Mata Pisau
Menghindari gula sepenuhnya bukanlah solusi. Glukosa dibutuhkan tubuh, terutama oleh sistem saraf pusat. Kekurangan gula justru bisa membuat kita sulit berkonsentrasi dan mudah lelah. Seperti dua sisi mata pisau, gula bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan, namun bermanfaat bila dikonsumsi secukupnya.
Kementerian Kesehatan RI dalam Permenkes No. 30 Tahun 2013 merekomendasikan batas konsumsi gula harian sebesar 50 gram atau setara 4 sendok makan per orang. Artinya, kesadaran bukan berarti paranoia. Yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan dalam mengonsumsi, bukan ketakutan berlebihan.
Penutup: Bijak, Bukan Fobia
Stigma terhadap gula perlu ditinjau ulang secara rasional. Gula bukan musuh, melainkan sahabat tubuh jika digunakan dengan bijak. Maka, daripada memusuhi gula, lebih baik kita memahami peran dan batas amannya. Edukasi gizi dan gaya hidup sehat menjadi kunci utama menjaga tubuh tetap bertenaga tanpa harus terjebak dalam ketakutan semu terhadap makanan manis.





